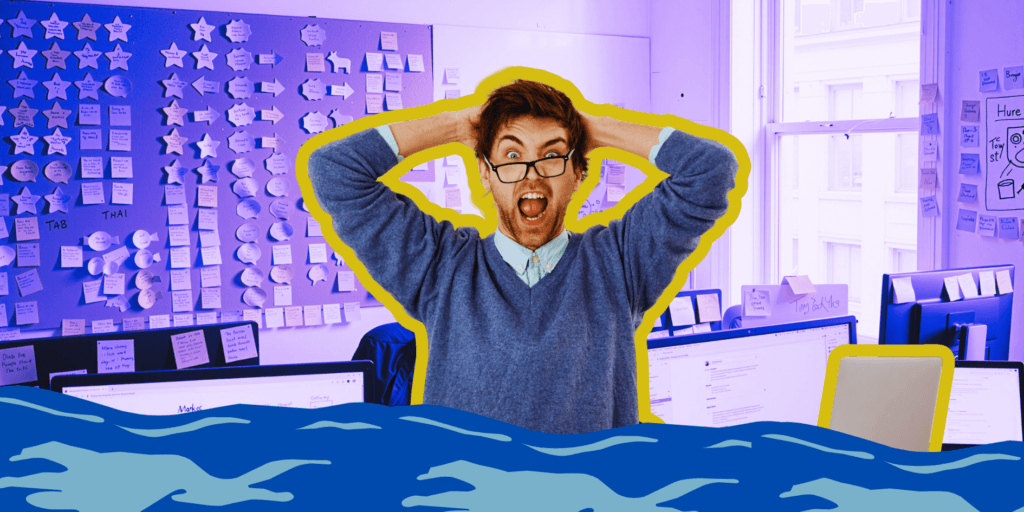Bagi pekerja di Jakarta dan sekitarnya, musim hujan bukan cuma soal jas hujan dan payung. Genangan air yang rutin mampir tiap tahun – atau belakangan, terasa tiap bulan – tidak hanya menghambat aktivitas, tapi juga pelan-pelan menambah beban lain yang jarang dibicarakan: kesehatan mental.
Saat hujan turun deras, pikiran kita jarang benar-benar fokus pada pekerjaan. Di sela rapat atau menatap layar laptop, muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih sunyi: pulang lewat mana? rumah aman nggak? bakal sampai jam berapa?.
Badan masih di kantor, tapi pikiran sudah melompat ke jalanan yang tergenang, transportasi yang tersendat, dan pesan dari rumah yang bikin cemas.
Banjir Jakarta: Rutinitas Musim Hujan
Jakarta memang punya kerentanan banjir yang tinggi. Curah hujan ekstrem, sistem drainase yang belum merata, serta padatnya wilayah permukiman membuat genangan air cepat meluas. Jalan protokol, kawasan perkantoran, hingga permukiman padat kerap terdampak. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas warga—terutama pekerja—langsung terganggu.
Dalam beberapa tahun terakhir, banjir tak lagi terasa sebagai kejadian langka. Di awal 2026 misalnya, puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali terendam. Di beberapa titik Jakarta Selatan dan Timur, ketinggian air bahkan dilaporkan mencapai lebih dari dua meter.
Ketika Perjalanan Kerja Jadi Sumber Stres

Banjir mengubah rutinitas sederhana menjadi sumber tekanan tambahan. Contohnya berangkat dan pulang kerja. Genangan di berbagai wilayah dan ruas jalan di Jakarta membuat mobilitas terganggu, transportasi umum tersendat, dan waktu tempuh yang tak bisa diprediksi membuat hari kerja terasa lebih panjang dari seharusnya.
Bayangkan berdesakan di stasiun pada hari normal saja sudah cukup menguras energi. Apalagi dalam kondisi banjir yang seringkali membuat jadwal KRL terganggu, rute bus terpaksa dialihkan, dan jalan alternatif ikut macet. Banyak pekerja berada dalam posisi serba salah: tetap berangkat dengan risiko terlambat dan kelelahan, atau memilih absen jika memungkinkan.
Banjir dan Kesehatan Mental Pekerja
Tekanan ini tidak berhenti di soal waktu. Kekhawatiran tentang kondisi rumah, keluarga yang mungkin terdampak, hingga rasa tidak aman di perjalanan, ikut membebani pikiran. Stres semacam ini menumpuk di atas tekanan kerja harian yang sudah lebih dulu ada.
Dalam konteks yang lebih luas, dampak psikologis bencana alam bukan hal sepele. Sebuah tinjauan di Journal of the American Medical Association yang terbit pada 2013 menyebutkan bahwa sepertiga atau lebih individu yang terdampak bencana alam berpotensi mengalami gangguan stres atau masalah kesehatan mental lainnya.
Banjir juga membuat tubuh dipaksa siaga lebih lama. Perjalanan kerja yang biasanya butuh satu jam, bisa molor jadi dua jam atau lebih. Di situasi ini, kita mau tidak mau harus duduk di kendaraan dengan kondisi lelah. Sementara, pikiran tak bisa benar-benar rileks.
Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan ini bahkan berujung tragedi. Seperti kasus pengemudi yang ditemukan meninggal di dalam mobilnya karena terjebak banjir dan kemacetan parah di Grogol Petamburan.
WFH: Solusi Sementara yang Tidak Selalu Merata

Sebagai respons terhadap perubahan cuaca ekstrem dan banjir, pemerintah DKI Jakarta mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja fleksibel atau WFH bagi pekerja di sektor yang memungkinkan. Di atas kertas, kebijakan ini terdengar masuk akal: mengurangi mobilitas, menjaga keselamatan, dan memberi ruang bernapas bagi pekerja.
Namun di lapangan, tidak semua pekerja punya kemewahan yang sama. Banyak jenis pekerjaan yang tak bisa dilakukan secara daring. Tidak sedikit pula perusahaan yang tetap menuntut kehadiran fisik demi alasan operasional. Akibatnya, beban banjir kembali jatuh pada kelompok pekerja yang pilihan kerjanya paling terbatas.
Yang Tergenang Bukan Cuma Jalanan
Banjir di Jakarta bukan hanya persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan pompa air atau pengalihan arus lalu lintas. Ia juga menyentuh sisi yang jarang dibicarakan: kesehatan mental pekerja yang mencoba bertahan di tengah bencana.
Ketika banjir datang, perjalanan kerja bukan lagi rutinitas sederhana. Ia berubah menjadi perhitungan, kecemasan, dan penundaan. Tubuh lelah dipaksa bertahan lebih lama, sementara ruang untuk bernapas semakin sempit.
Di tengah kondisi ini, yang kita butuhkan bukan hanya solusi struktural, tapi juga pengakuan sederhana: bahwa lelah karena banjir itu nyata. Dan bahwa menjaga kesehatan mental pekerja sama pentingnya dengan menjaga jalanan tetap kering.